Pada satu titik, kebanyakan orang pernah mengalami momen yang sama: Jari-jari kita terus menggeser layar, mata terpaku, waktu melayang. Dua jam kemudian, tidak ada satu pun hal yang benar-benar maknai. Di balik kesibukan virtual itu, kita sering tidak mendapatkan apa-apa, kecuali rasa senang sesaat yang terus menerus menuntut dipuaskan. Intensitas konten yang cepat : TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, memformat ulang cara pengguna internet mengonsumsi informasi. Byung-Chul Han, filsuf asal Korea, menyebut fenomena ini sebagai the burnout society, masyarakat kelelahan yang dicekik oleh tuntutan produktivitas dan keterhubungan konstan. Di dalamnya, perhatian manusia menjadi sumber daya yang dipanen tanpa henti.
TikTok misalnya, dirancang sebagai jalur tak berujung dari video pendek, memanfaatkan algoritma yang belajar dengan sangat cepat apa yang membuat seseorang tertahan beberapa detik lebih lama. Tristan Harris, mantan desainer etika di Google, menjelaskan bagaimana platform-platform ini memanfaatkan variable rewards, teknik yang diambil dari mesin judi, untuk membuat orang tak bisa berhenti. Ada kejutan, ada rasa penasaran, ada humor yang tiba-tiba muncul di layar. Semua dibungkus dalam paket singkat yang terasa ringan tetapi membuat kecanduan.
Kita bisa bayangkan, seseorang membuka TikTok “hanya 5 menit sebelum tidur.” Lima puluh video kemudian, satu jam berlalu, dan otak justru terlalu terangsang untuk bisa tertidur. Di kereta, anak muda menonton reels lucu sambil tertawa kecil, tetapi tak melihat pemandangan kota yang melintas. Di meja makan keluarga, beberapa anggota sibuk menonton YouTube Shorts, dengan wajah diterangi cahaya layar, sementara percakapan sepi. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota besar. Bahkan di daerah-daerah, Wi-Fi gratis di taman atau alun-alun kini penuh oleh anak muda yang asyik scrolling video pendek.
Keseruan itu bukannya berjalan baik-baik saja, karena ada kelelahan yang mungkin tidak dirasakan. Microsoft (2015) menunjukkan rentang perhatian manusia menurun drastis dalam dekade terakhir, dari 12 detik menjadi hanya 8 detik. Namun data kuantitatif saja tidak cukup menangkap dampak emosionalnya. Ada kelelahan mental yang muncul karena otak terus dihadapkan pada stimulus cepat. Adam Alter, penulis buku Irresistible, menjelaskan bahwa scroll tak berujung menciptakan ilusi progress, padahal otak tidak pernah mencapai titik selesai. Hal inilah yang memicu rasa tidak puas sekaligus kelelahan mental.
Sherry Turkle, psikolog sosial MIT, menambahkan bahwa dunia digital membuat manusia berada dalam kesendirian meski bersama dan saling terhubung : alone together..Turkle pernah menceritakan sebuah eksperimen sosial: sekelompok orang makan malam bersama, tetapi diminta tidak membuka ponsel. Hasilnya, banyak yang merasa canggung, seolah tidak punya bahan obrolan. Artinya, bukan hanya kehadiran digital yang mencuri perhatian, tetapi juga mengikis kemampuan manusia untuk terlibat dalam keheningan yang produktif atau percakapan spontan. Di meja makan, di kereta, di ruang tunggu, orang-orang hadir, tapi pikirannya melayang ke notifikasi, scroll, dan pesan singkat. Interaksi manusia menjadi tipis, terfragmentasi, dan kehilangan lapisan emosionalnya.
Sosiolog Zygmunt Bauman menyebut gejala ini sebagai liquid modernity, hidup yang cair, serba cepat, dangkal, ketika hubungan antar manusia kehilangan daya tahan. Kontak sosial kini lebih banyak terjadi lewat platform yang mengutamakan performa: story, likes, views. Hubungan menjadi transaksi perhatian, bukan keintiman. Setiap interaksi harus singkat, catchy, layak bagikan. Erving Goffman dalam The Presentation of Self in Everyday Life pernah membahas bagaimana manusia selalu “berpentas” di hadapan orang lain. Namun di era digital, pentas itu semakin intens, cepat dan melelahkan.
Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang sering merasa lelah tanpa aktivitas nyata. Seorang pekerja kantoran bisa pulang kerja, merasa seolah belum sempat istirahat, meski secara fisik hanya duduk di kursi sepanjang hari. Kepalanya penuh dengan notifikasi, email yang belum dijawab, scroll media sosial, dan tab yang tak kunjung ditutup. Cal Newport, penulis Digital Minimalism, menyebut ini sebagai “keterpecahan perhatian”, otak terus berpindah konteks, membuatnya lebih cepat lelah meski tidak melakukan kerja fisik.
Di konteks inilah gagasan slow media mulai tumbuh: dorongan untuk melambat, untuk berhenti, untuk hadir utuh. Bukan sekadar melawan teknologi, tetapi melawan kelelahan yang timbul dari teknologi. Slow media muncul sebagai penawar atas rasa jenuh terhadap kecepatan, menawarkan ruang di mana manusia bisa membaca lebih dalam, mendengarkan lebih lama, dan berpikir lebih perlahan. Bukan demi romantisasi masa lalu, tetapi demi mempertahankan kesehatan mental dan relasi sosial yang lebih manusiawi.
Slow Media, Soal menyikapi waktu dan kehadiran
Seringkali slow media disalahpahami hanya sebagai konten yang panjang. Padahal, slow media adalah sebuah penyikapan hidup. Sikap yang membawa prinsip bahwa tidak semua hal harus disampaikan dalam 60 detik. Bahwa memahami dan mengambil makna membutuhkan waktu. Bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas. Slow media lahir dari sebuah keinginan, bahwa manusia harus merebut kembali ruang kontemplasi yang selama ini semakin langka dan terkikis oleh kecepatan algoritma.
Banyak yang menganggap lambat identik dengan kuno, seolah slow media hanya nostalgia zaman cetak. Padahal, slow media adalah wujud kesadaran kritis atas bagaimana teknologi digital dirancang. Jennifer Rauch, dalam bukunya Slow Media: Why Slow is Satisfying, Sustainable and Smart, menguraikan bahwa slow media bukan gerakan anti-teknologi. Slow media justru mengajak manusia mengatur hubungan kita dengan media digital, untuk tidak sekedar menjadi objek yang selalu ditarik oleh notifikasi dan algoritma.
Rauch menggunakan istilah mindful media engagement , sebuah cara berinteraksi dengan media secara sengaja, memilih apa yang benar-benar ingin dibaca, didengar, atau ditonton, bukan sekadar menerima apa pun yang dilempar algoritma. Sikap ini paralel dengan gagasan digital minimalism yang diajukan oleh Cal Newport, yang menekankan bahwa teknologi seharusnya menjadi alat, bukan tuan.
Ilustrasi nyata muncul di banyak komunitas daring. Misalnya, Longreads, yang setiap minggu mengkurasi tulisan panjang dari seluruh dunia. Artikel yang mereka rekomendasikan sering kali lebih dari 3.000 kata, membahas satu topik dengan teliti, mulai dari investigasi korupsi di negara berkembang hingga esai personal tentang kehilangan. Bagi pembaca Longreads, lambat bukan membuang waktu, tetapi memberi ruang bagi keterhubungan emosional dan pemahaman yang lebih menyeluruh
Salah satu contoh paling ikonik adalah artikel panjang di The Atlantic tahun 2021 berjudul The Pandemic of Fear oleh Ed Yong. Dengan lebih dari 7.000 kata, artikel ini adalah bentuk laporan angka COVID-19 yang secara dalam menyelami trauma psikologis masyarakat, keretakan kepercayaan publik, dan konsekuensi sosial jangka panjang. Tulisan semacam ini tidak mungkin ditangkap dalam format TikTok berdurasi 30 detik. Tetapi justru di sanalah kekuatan slow media: ia menghadirkan nuansa, konteks, dan kompleksitas.
Slow media juga dipraktekkan di ranah podcast. Lex Fridman Podcast kerap menghadirkan tokoh besar, mulai dari ilmuwan hingga filsuf, dalam percakapan sepanjang 2 hingga 4 jam. Ketika Fridman berbicara dengan penulis seperti Yuval Noah Harari, diskusi merambah ke sejarah umat manusia, AI, hingga eksistensialisme. Tidak ada tekanan untuk memotong obrolan demi clickbait. Tidak ada musik dramatis setiap 15 detik. Para pendengarnya rela meluangkan waktu mendengarkan bukan sekadar untuk informasi, tetapi untuk menikmati proses berpikir bersama.
Case study lain datang dari dunia video essay di YouTube. Kanal seperti ContraPoints atau Nerdwriter memproduksi video sepanjang 20-40 menit, mengupas isu-isu sosial, budaya pop, hingga filsafat dengan pendekatan sinematik. ContraPoints, misalnya, membahas tema berat seperti Cancel Culture dengan skenario, kostum, humor, dan argumentasi yang sangat mendalam. Video seperti ini ditonton jutaan kali, menunjukkan ada publik yang lapar akan narasi panjang dan konten yang tidak direduksi jadi potongan-potongan sekian detik.
Sebenarnya slow media bukan persoalan panjang artikel belaka. Nicholas Carr, penulis The Shallows, mengingatkan bahwa konsumsi media cepat bukan hanya persoalan waktu, tetapi juga mempengaruhi cara kerja otak. Kebiasaan scroll cepat melemahkan koneksi saraf yang diperlukan untuk membaca mendalam. Otak menjadi terbiasa hanya memproses potongan kecil informasi, kehilangan kemampuan untuk membangun pemahaman kompleks. Slow media, kata Carr, adalah latihan mental untuk kembali membangun “deep reading brain.”
Membaca esai panjang, mendengarkan diskusi filosofis, atau menonton video essay adalah bentuk dari latihan kesabaran, fokus, dan ketahanan mental. Sama seperti berlari jarak jauh melatih paru-paru, slow media melatih kapasitas berpikir kritis dan empati. Di tengah budaya instan, ia menjadi ruang resistance, tempat manusia mengambil kembali waktu dan atensi mereka dari cengkeraman algoritma.
Fenomena slow media juga mulai diadopsi brand besar. Patagonia, misalnya, dalam beberapa kampanye memilih membuat film dokumenter panjang tentang konservasi alam, daripada iklan 30 detik. Mereka memahami bahwa cerita panjang membangun koneksi emosional lebih kuat, dan loyalitas yang lebih tulus. Ini menunjukkan bahwa slow media tidak hanya idealisme, tetapi juga bisa menjadi strategi komunikasi yang efektif, asalkan dijalankan dengan tulus.
Konsep slow media memang menjadi antitesa terhadap mainstream di ranah digital. Karena algoritma platform sosial tidak berpihak pada pembacaan yang lambat. Platform seperti Instagram atau TikTok dirancang untuk proses interaksi yang cepat. Video 20 menit sulit bersaing dengan video lucu berdurasi 15 detik. Bahkan YouTube, meskipun menjadi lahan video panjang, tetap lebih mengutamakan watch time yang padat. Bagi pembuat konten slow media, kondisi ini berarti sering menjadi dilema: Ketap setia pada narasi yang komprehensif dan dalam, atau menyerah pada format cepat demi distribusi pesan yang lebih luas.
Jennifer Rauch menjelaskan bahwa slow media mungkin tidak pernah menjadi arus utama. Tetapi ia selalu punya tempat. Seperti ruang alternatif, kecil tetapi kehadirannya menjadi penting. Karena di sanalah orang-orang yang menolak hidup serba cepat menemukan komunitasnya: mereka yang masih percaya bahwa waktu, pemikiran, dan kehadiran adalah hal-hal yang layak diperjuangkan.
Ironi Slow Media, apakah melambat hanya untuk mereka yang punya privilege?
Konsep slow media bukannya tanpa kritik. Ada pertanyaan substansial yang tidak bisa diabaikan: apakah lambat hanya mungkin bagi mereka yang punya waktu, pendidikan, dan privilege? Apakah orang-orang yang bekerja dua shift, yang lelah setelah 12 jam di pabrik atau kantor, punya energi membaca esai 10.000 kata atau mendengarkan podcast tiga jam?
Richard Sennett, dalam karyanya The Fall of Public Man, menunjukkan bahwa kehidupan urban menuntut ritme cepat. Warga kota dibentuk oleh pola kerja yang padat, perjalanan panjang, dan tuntutan sosial yang makin tak kenal waktu. Dalam lanskap ini, slow media berisiko menjadi lifestyle eksklusif, dinikmati oleh mereka yang punya waktu untuk lambat, yang punya ruang mental untuk merenung. Sennett menulis bahwa: the city encourages people to look away from one another, menjelaskan bagaimana interaksi sosial urban makin dangkal, tidak hanya karena teknologi, tetapi juga karena struktur waktu yang makin kejam.
Pierre Bourdieu, sosiolog Prancis, juga penting disebut. Melalui konsep “capital culturel,” ia menjelaskan bahwa tidak semua orang memiliki modal budaya untuk menikmati konten lambat. Membaca longform journalism, menonton dokumenter panjang, atau mendengarkan diskusi filsafat butuh modal literasi, kebiasaan membaca, dan ruang waktu. Bourdieu mengingatkan bahwa preferensi budaya sering kali menjadi penanda kelas sosial, bukan melulu soal selera. Slow media, dalam konteks ini, berpotensi menciptakan gap budaya baru antara “the slow elites” dan “the fast masses.”
Ilustrasi nyata terlihat dalam pola konsumsi media. TikTok dan Reels, dengan durasi 15–60 detik, sangat populer di hampir semua kalangan. Konten cepat terasa ringan, tidak menyedot energi kognitif besar. Saat istirahat makan siang, seorang karyawan di pabrik mungkin lebih memilih menonton 10 video lucu daripada membaca artikel panjang yang menguras kerja otak. Bukan karena tidak mau, tetapi karena otaknya terlalu lelah menghadapi masalah kerja dan keseharian. Sementara di sisi lain, di kafe-kafe kelas urban, tampak orang duduk berjam-jam membaca esai panjang atau buku. Begitulah, hari-hari yang super sibuk ini, waktu menjadi privilege. Data mendukung realitas ini. Reuters Digital News Report (2022) mencatat bahwa hanya 13% pembaca global yang rutin mengonsumsi artikel panjang. Mayoritas lebih memilih berita pendek, highlight, atau video singkat. Bahkan di negara maju, audiens longform journalism cenderung berasal dari kelompok berpendidikan tinggi dan berpendapatan lebih baik.
Di sisi lain, Sherry Turkle mengingatkan bahwa slow media bukan hanya soal waktu panjang. Turkle berbicara tentang “sacred spaces”—momen kecil di mana seseorang memutus koneksi digital dan memilih hadir sepenuhnya. Lambat bisa hadir dalam bentuk sederhana: membaca artikel panjang 10 menit di kereta, mendengarkan podcast sambil berjalan kaki, atau mematikan notifikasi setengah jam sebelum tidur untuk membaca satu bab buku. Jennifer Rauch menekankan hal yang sama, bahwa slow media bisa diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, bukan semata konsumsi kaum intelektual.
Salah satu case study yang menarik adalah fenomena newsletter panjang di platform seperti Substack. Penulis independen seperti Anne Helen Petersen atau Casey Newton membangun komunitas pembaca yang rela meluangkan waktu membaca esai panjang setiap minggu. Petersen, misalnya, menulis panjang lebar soal budaya kerja berlebihan (burnout culture), isu gender, dan politik pop culture. Audiensnya bukan semata akademisi, tetapi juga pekerja kantoran biasa, perawat, hingga guru yang merasa media cepat tidak lagi memuaskan kebutuhan mereka akan analisis yang lebih mendalam.
Contoh lain datang dari Indonesia. Majalah Tempo, The Conversation Indonesia atau Project Multatuli misalnya, tetap berusaha memproduksi artikel panjang, meski berada di tengah tuntutan konten cepat. Artikel panjang tentang mafia tambang misalnya, menjadi banyak dibaca karena publik haus penjelasan komprehensif. Cerita ini menunjukkan, bahwa hasrat akan kedalaman tidak sepenuhnya mati, meskipun algoritma mendorong kita ke arah cepat.
Tapi, tantangan tetap besar. Slow media sering terjebak di balik paywall. The New York Times, The Atlantic, hingga Medium mulai membatasi akses konten-konten yang in-depth hanya bagi pelanggan berbayar. Bagi banyak orang, ini menjadi tembok ekonomi yang membatasi akses terhadap konten berkualitas. Bahkan podcast panjang pun kini banyak yang beralih ke sistem berbayar (Patreon, Substack Audio).
Tristan Harris menambahkan dimensi lain. Bagi kelas pekerja, lambat tak sekedar mahal dari sisi uang, tetapi juga dari sisi biaya waktu sosial. “People living paycheck-to-paycheck have no margin for intentional downtime,” kata Harris. Waktu senggang mereka habis untuk kebutuhan dasar: istirahat, keluarga, pekerjaan tambahan. Lambat menjadi kemewahan. Namun, di sinilah justru letak nilai slow media. Meski mungkin bukan untuk semua orang, slow media menyediakan ruang alternatif. Sebagai sebuah perlawanan, Slow Media juga menjadi pengingat bahwa manusia tidak harus selalu hidup dalam ritme algoritma. Bahwa makna, empati, dan keterhubungan emosional membutuhkan waktu. Seperti yang diungkapkan Nicholas Carr, lambat tidak harus eksklusif. Ia bisa dimulai dari hal kecil: membaca artikel panjang seminggu sekali, menonton dokumenter di akhir pekan, atau mendengarkan podcast panjang sambil membersihkan rumah.
Masa depan slow media mungkin bukan soal menjadi arus utama. Tapi lebih pada mempertahankan ruang-ruang kontemplatif yang masih memungkinkan manusia berpikir lebih dalam. Karena tidak semua harus cepat. Tidak semua harus viral. Dan di situlah slow media menemukan perannya.
Slow media sebagai bentuk kehadiran: Ruang yang harus dipertahankan
Slow media membantu manusia untuk hadir. Hadir tidak hanya di ruang digital, tetapi hadir di dunia fisik, hadir dalam percakapan bahkan hadir dalam kesunyian. Sherry Turkle pernah menjelaskan bahwa keintiman manusia tumbuh dari jeda dan keheningan, sesuatu yang hampir punah di siklus trend cepat dan teror notifikasi. Bagi Turkle, keheningan bukan kekosongan, tetapi ruang bagi pikiran untuk memproses, merenung, dan terhubung secara emosional dengan sesama.
Fenomena ini sangat nyata dalam kehidupan kontemporer. Kita melihat orang-orang duduk bersama di kafe, tetapi masing-masing sibuk dengan screen. Bahkan saat menonton konser, sebagian lebih sibuk merekam video daripada benar-benar menikmati musik. Psikolog Adam Grant menyebut kondisi ini sebagai “absent presence” , tubuh memang ada dan hadir, tetapi pikiran di tempat lain. Slow media, dalam kondisi seperti ini, bisa menjadi tindakan radikal. Memilih hadir sepenuhnya dalam satu momen, bukan sekadar “menyaksikan” sambil terpecah perhatian.
Slow media juga menawarkan ruang untuk berpikir kritis. Ketika dunia dibanjiri opini cepat, kemarahan cepat, dan budaya cancel, slow media menyediakan waktu untuk mempertimbangkan argumen, membaca konteks, dan memahami kompleksitas. Podcast panjang seperti Conversations with Tyler menampilkan intelektual dari berbagai disiplin yang jarang muncul di media cepat. Di sana, ide-ide diulik bukan untuk memicu clickbait, tetapi untuk benar-benar menjelaskan dunia.
Contoh menarik muncul di kanal YouTube Philosophy Tube yang dijalankan oleh Abigail Thorn. Video-videonya berdurasi panjang, penuh narasi dramatis, dan membahas isu-isu pelik seperti identitas gender, keadilan sosial, hingga etika teknologi. Tidak sedikit yang durasinya di atas 40 menit. Meski tidak sepopuler TikTok, kanal ini menciptakan komunitas yang merindukan ruang diskusi panjang dan mendalam. Orang-orang rela duduk lama, merenungkan argumen, dan berdialog di kolom komentar dengan sopan, jauh dari debat kasar media sosial arus utama.
Tapi harus kita akui, kenyataanya platform-platform digital tidak mendukung lambat. Algoritma TikTok, YouTube, Instagram, dirancang untuk memanjangkan waktu screen time dengan cara memecah perhatian menjadi fragmen-fragmen kecil. Semakin lama seseorang bertahan, semakin banyak iklan yang bisa dijual, semakin besar perputaran ekonomi digital. Shoshana Zuboff, dalam karyanya The Age of Surveillance Capitalism, mengungkap bagaimana setiap detik perhatian manusia ditangkap, dianalisis, dan dimonetisasi. Algoritma tidak sekadar menyajikan apa yang disukai pengguna, tetapi membentuk apa yang dianggap layak untuk disukai.
Sebuah studi dari Harvard Business Review (2021) menunjukkan bahwa rata-rata pengguna TikTok membuka aplikasi lebih dari 19 kali sehari, dengan durasi total sekitar 89 menit. Bukan karena kontennya selalu menarik, tetapi karena desain platform membuat orang takut ketinggalan. Dalam ekosistem seperti ini, slow media menjadi ancaman langsung terhadap model bisnis platform. Lambat tidak menghasilkan cukup impresi, tidak memicu engagement cepat, dan tidak memunculkan impuls konsumsi instan.
Diantara siklus kehidupan yang cepat, selalu ada ruang bagi lambat. Sama seperti toko buku independen yang bertahan di tengah gempuran e-commerce, slow media bertahan karena ada orang-orang yang rindu dengan makna. Mereka, orang-orang yang tidak ingin hidupnya semata ditentukan dan diarahkan oleh siklus platform media sosial dengan algoritmanya. Orang-orang ini hampir pasti minoritas, tetapi minoritas yang selalu ada di setiap zaman. Zygmunt Bauman, dalam Liquid Modernity, menyebut kelompok semacam ini sebagai retentive individuals — mereka yang menolak terbawa arus, yang pencarian-pencarian yang dalam ketimbang hanyut dalam loop kecepatan wacana digital.
Sekali lagi, slow media tidak akan pernah menjadi arus utama. Namun mungkin, ia tidak perlu menjadi arus utama. Nilainya justru terletak pada posisinya sebagai ruang alternatif. Seperti adalah oasis di tengah padang pasir trend dan notifikasi. Tempat orang mengambil napas, berpikir ulang, lalu kembali ke dunia dengan pandangan yang lebih jernih. Persis seperti pengalaman pembaca yang mengisahkan bagaimana satu artikel panjang di The Conversation mengubah cara mereka memandang politik luar negeri, atau satu episode podcast panjang membuat mereka memutuskan mengubah pola hidup.
Ilustrasi lain bisa dilihat pada komunitas pembaca newsletter panjang di platform seperti Substack, yang kebetulan tidak populer di negeri kita. Penulis seperti George Saunders, seorang penulis fiksi ternama, kini menggunakan Substack untuk menulis surat panjang kepada pembacanya. Tidak jarang tulisannya lebih dari 3.000 kata, membahas proses kreatif, pandangan hidup, atau isu sosial. Para pembaca membalas dengan komentar panjang, seolah berbicara pada sahabat lama. Bagi mereka, slow media menjadi ruang kehadiran emosional, bukan sekadar konsumsi informasi.
Selain itu, media seperti Aeon dan Emergence Magazine mempertahankan tradisi slow media dengan menerbitkan esai panjang, seringkali disertai foto, ilustrasi, dan desain visual yang indah. Mereka percaya membaca bukan hanya proses mental, tetapi juga pengalaman estetika. Desain lambat mereka mengundang pembaca untuk berhenti sejenak, menatap visual, merenungkan kata-kata, bukan hanya melewati konten secepat mungkin.
Slow media memang menghadapi risiko teralienasi dari publik lebih luas. Bourdieu mengingatkan bahwa akses terhadap media lambat sering kali dibatasi oleh kelas sosial dan latar pendidikan. Slow media, jika tidak hati-hati, justru bisa menjadi elitisme. Tantangan slow media di masa depan adalah bagaimana menciptakan keterlibatan yang luas dan terbuka, menjangkau audiens yang lebih luas tanpa kehilangan kedalaman.
Selalu ada alasan untuk menjadi optimis. Jennifer Rauch percaya bahwa meski lambat tidak populer, ia akan selalu memiliki tempat karena manusia pada dasarnya mencari makna. Slow media tidak sekadar menawarkan informasi, tetapi menghadirkan rasa terhubung, dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan dunia
Slow media bukan utopia. Ia memiliki tantangan, termasuk risiko menjadi eksklusif. Namun di balik kerumitannya, slow media mengingatkan satu hal mendasar: kehidupan tidak harus selalu dijalani dalam kecepatan tinggi. Ada nilai dalam keterlambatan, dalam keheningan, dalam percakapan. Ketika dunia digital terus memaksa manusia untuk berlari, memilih untuk melambat adalah bentuk keberanian. Mungkin essay tidak akan viral, tidak menghasilkan views yang fantastis. Tapi ia memberi ruang bagi manusia untuk menjadi utuh.
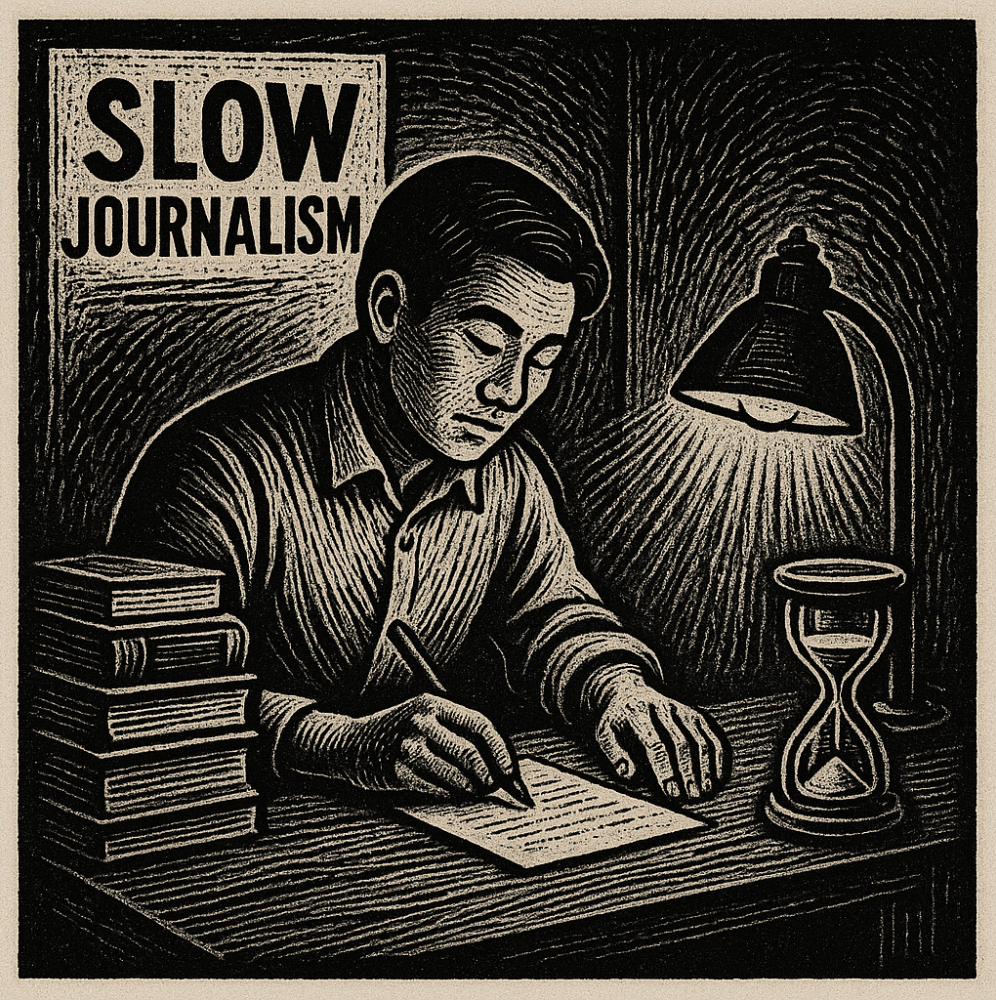
Leave a comment